Dalam kajian Maqashid Syariah kita mengenal istilah “Adh-Dharuriyyat al Khams” (lima perkata darurat), yaitu Agama, Akal, Jiwa, Keturunan dan Harta.
Kelima perkara ini senantiasa dijaga oleh Syariat, karena ia bersifat primer, sangat penting dan darurat untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia dan kesuksesan mereka di akhirat. Sehingga, manakala kelima perkara ini, atau salah satunya dalam kondisi terancam, situasi itu dapat dinyatakan sebagai “situasi darurat”. Dan dalam kaidah fikih dikatakan, “Adh-Dharuratu tubiihu al Mahdzuraat” (Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang).
Dalam konteks politik di negeri ini, secara faktual, pemimpin dipilih melalui mekanisme politik yang mengacu kepada sistem demokrasi. Kita pun mengetahui bahwa demokrasi bukan dari Islam, bertentangan dengan syariat, dan bahkan, asas-asasnya mengandung kekufuran. Namun, berpartisipasi dalam sistem ini tidak menjadi haram secara mutlak. Dalam situasi darurat, perbuatan itu dapat dilegalkan.
Memiliki pemimpin kafir atau sosok yang anti Islam tentu sebuah madhorot yang mengancam eksistensi “lima perkara darurat diatas”. Betapa banyak negeri Islam yang berubah menjadi negeri kafir karena sebab penguasa atau pemimpin yang kafir, seperti Spanyol, Iran dan lain-lain. Betapa banyak juga kaum muslimin yang kehilangan nyawa dan harta mereka gara-gara dipimpin oleh orang kafir, seperti yang terjadi di Suria, Burma dan lain-lain.
Dari sisi agama sangat jelas. Pemimpin kafir atau anti Islam akan menghalangi manusia dari jalan Allah, membatasi ruang gerak pada dai untuk berdakwah, membiarkan kebatilan menyebar dimana-mana, bahkan bisa jadi sampai taraf membantai ahli Islam.
Maka, memilih untuk berpartisipasi dalam produk demokrasi seperti pemilu atau pilpres, bukan sikap seorang yang bermental tempe, ABG atau kabayan, bukan pula sikap takut kepada selain Allah. Sangat keji tuduhan-tuduhan seperti itu padahal memilih sikap untuk berpartisipasi pun didukung oleh fatwa banyak para ulama, baik secara personal atau kolektif. Memilih berpartisipasi justru menunjukkan sikap waspada, berorientasi mulia dan beritikad menunaikan wasiat Syariat untuk mengupayakan Ishlah (perbaikan) dan taghyiir al munkar (merubah kemungkaran) sesuai dengan kemampuan.
Dan satu hal yang harus difahami, bahwa perbaikan membutuhkan proses dan merubah kemungkaran tidak berarti melenyapkan kemungkaran secara sempurna, namun juga bermakna mengurangi kemungkaran dan potensi bahaya yang mengancam. Sikap memilih untuk berpartisipasi juga dalam rangka mengamalkan firman Allah, “Fattaqullaha mash tatho’tum” (Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan).
Berbicara tentang demokrasi, setidaknya dapat kita tilik dari dua sisi. Yang pertama, adalah berbicara tentang demokrasi dari sisi konsep dan asas demokrasi, serta apa yang menjadi pandangan dan keyakinan kita terhadapnya. Dan ini jelas, sebagaimana yang telah diutarakan di atas.
Yang kedua, berbicara tentang demokrasi dari sisi sikap dan respon kita terhadap sistem tersebut, yang secara faktual, tidak ada sistem politik yang lain di negeri ini. Sikap atau respon terhadap sesuatu, tentu tidak hanya ditentukan oleh variable tunggal; yaitu keyakinan. Sikap atau respon, selain ditentukan oleh keyakinan, juga dipengaruhi oleh variable-variable yang lain, yaitu situasi dan kondisi yang melingkupi saat kita harus mengambil sikap dan menentukan respon.
Maka terkadang, hal yang kita yakini buruk, bisa jadi kita lakukan. Dan sebaliknya, hal yang kita pandang baik, bisa jadi kita tinggalkan. Kapan kita memilih yang buruk? dan kapan kita ternyata meninggalkan yang baik? Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar kemunculan konsep Syariat, “Jalbul Mashalih wa Taktsiiruhaa wa Dar`ul Mafasid wa Taqliiluhaa” (Mendatangkan maslahat dan memperbanyaknya, serta mencegah bahaya dan menguranginya). Ya, pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mafsadah inilah jawabannya.
Kita bisa saja melakukan sesuatu yang buruk, untuk meraih kemaslahatan yang besar, atau untuk mencegah keburukan yang lebih parah. Sebagaimana kita juga terkadang meninggalkan yang baik, untuk meraih kebaikan yang lebih besar, atau untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Sehingga dalam Syariat juga terdapat kaidah, “Tarkul waajib limaa huwa aujab” (Meninggalkan yang wajib untuk meraih yang lebih wajib), “Irtikaabu akhaffu adh-dhararain” (memilih kemadaratan teringan), atau “Irtikaabu al mafsadatish shughraa li daf’il mafsadatil kubraa” (memilih kemadaratan yang kecil untuk mencegah kemadaratan yang besar)
Begitu pun halnya dalam sikap dan respon kita terhadap demokrasi, walaupun kita menganggap demokrasi adalah keburukan, namun tidak selalu berarti sikap yang kita pilih adalah meninggalkannya secara mutlak. Jika ia sejalan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah syariat diatas, ia bisa menjadi legal. Jika tidak, maka ia haram sebagaimana asalnya.
Nilai dan kaidah yang saya sampaikan diatas bukan berdasar pada akal-akalan semata. Terdapat banyak dalil dari Al Qur`an dan Sunnah yang mengafirmasi legalitas kaidah diatas. Diantaranya:
Pertama: Kisah Ammar bin Yasir yang mengatakan kata-kata kufur karena jiwanya teracam. Saat hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Ammar, “Bagaimana keadaan hatimu?” “Tenang dalam keimanan”, Jawab Ammar. Beliau kemudian berkata, “Jika mereka kembali melakukan hal itu, maka ulangilah perbuatanmu itu.” Kejadian ini menjadi sebab turunnya firman Allah (yang artinya),
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (An Nahl: 106)
Kedua: Firman Allah tentang mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik (yang artinya),
“dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Al An’aam: 108)
Ibnu Katsir berkata,
قول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو
“Firman Allah melarang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang-orang beriman mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik, walaupun padanya ada kemaslahatan, namun hal itu akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar darinya, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencela sesembahan orang-orang beriman, yaitu Allah, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Dia.”
Ketiga: Nabi Yusuf ‘alaihissalam yang meminta jabatan kepada Raja Mesir. Allah berfirman menghikayatkan tentang Yusuf,
“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Yusuf: 55)
Menjadi bagian dari pemerintahan seorang raja kafir tentu saja mengandung keburukan, namun ketika ada kemaslahatan yang diharapkan dengan melakukannya, Nabi Yusuf pun melakukan hal itu, yaitu agar ia bisa mewujudkan keadilan dalam mengelola hasil-hasil bumi selama tujuh tahun masa paceklik.
Keempat: Rasulullah menyarankan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena di Mekah intimidasi kaum musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi. Negeri Habasyah adalah negeri kafir, tentu sesuatu yang madorot menetap di negeri kafir, namun manakala menetap di sana lebih baik daripada tinggal di kota Mekah, hal itu menjadi pilihan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kelima: Perjanjian Hudaibiyyah. Pada saat Rasulullah bersama kaum muslimin hendak menuju Mekah untuk melaksanakan Umrah, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy. Pada saat ini lah kemudian terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Saat akan dituliskan poin-poin perjanjian, delegasi orang Quraisy sempat menolak lafadz Ar-rahman dan Ar-rahiim, dua nama Allah. Begitu juga menolak lafadz “rasulullah” setelah nama Muhammad. Belum lagi poin-poin perjanjian itu secara lahir merendahkan kaum muslimin. Sehingga Umar sempat berkata, “Limaa nardhaa bid daniyyah?” mengapa kita rela dengan kerendahan?”
Mengapa semua itu dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal nampak secara lahir semua itu adalah keburukan? Lagi-lagi pertimbangannya adalah maslahat dan madhorot. Beliau ingin perjanjian itu terwujud, agar beliau dan kaum muslimin memiliki keluasaan untuk berdakwah tanpa ada gangguan dari orang-orang musyrik.
Keenam: ketika telah jelas bagi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallamhakikat sebagian orang-orang munafik dan keharusannya untuk dibunuh secara hukum syariat, beliau tidak melakukannya dan beralasan,
لايتحدثالناسبأنمحمدايقتلأصحابه
“Agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya.”(HR Bukhari)
Beliau tidak membunuhnya dalam rangka mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi Islam dan ahli Islam, juga dalam rangka mencegah datangnya keburukan yang lebih besar yang dapat timbul dari keburukan yang ditimbulkan dari tidak membunuhnya.
Hal itu karena jika orang-orang berbicara dengan pembicaraan seperti itu (Muhammad telah membunuh sahabatnya) dan berita tersebut menyebar, sementara sebabnya tidak mereka ketahui, maka yang demikian akan menjadi perkara yang dapat menjauhkan orang-orang musyrik dari masuk kepada agama ini. Karena pendengaran mereka telah dijejali dengan pembicaraan seperti ini, sehingga mereka menyangka bahwa selamat dari pembunuhan dengan masuk Islam itu tidak benar. Maka mereka lari dari agama ini dan menjauh sejauh-jauhnya.
Wallahu a’lam.
Publisher of the article by :http://abunamira.wordpress.com
Rewritten by : Rachmat Machmud end Republished by : Redaction
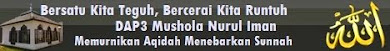



0 komentar:
Posting Komentar
= > Silakan Berkomentar Sesuai Tema Diatas
=> Berkomentar Dengan Link Hidup Tidak Akan di Publish
=> Dilarang Berkomentar SPAM
=> Tinggalkan Komentar Sangat Penting Untuk Kemajuan Blok ini